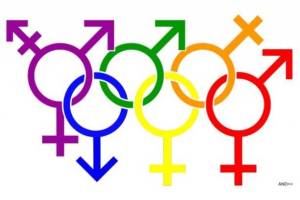Dewasa ini, isu mengenai Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) menjadi topik yang sangat populer pada bermacam wadah ekspresi, baik media massa maupun media sosial. Pro dan kontra terus mengemuka dengan berbagai argumennya yang tentu sama-sama diklaim valid. Namun, sesempit pengetahuan penulis, debat yang mengemuka cenderung menggunakan basis moral dan religi. Celakanya, definisi dan nilai artikulasi orang terhadap moral dan religi memiliki variasi yang cukup tinggi sehingga perdebatan tersebut cenderung tidak ada ujung pangkalnya.
Merujuk pada penelitian PEW research center (http://www.pewresearch.org/), negara-negara yang religius memang memiliki toleransi yang minimal terhadap perilaku LGBT. Semakin religius sebuah negara, semakin besar kecenderungan penolakannya atas LGBT. Indonesia, dalam riset tersebut, dikategorikan sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat religiusitas tinggi. Wajar saja nuansa penolakannya jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara yang dikategorikan kurang religius semisal Kanada, Spanyol, Jerman, dan Inggris. Akan tetapi, dengan nuansa debat berbasis moral dan religi tanpa basis data yang jelas, pihak yang berdebat pun pada gilirannya memiliki definisi kebenaran dan kepatutan yang berbeda yang hampir mustahil bertemu sapa.
Dalam artikel ini, kita tidak akan menjelajahi data kaum Sodom dan Gomorah serta melampirkan ayat betapa Tuhan membenci kaum ini sehingga memberikan azab yang ganas. Biarlah para ustaz yang bercerita. Di sini, penulis akan memaparkan analisis empiris sederhana berbasis data yang valid dan mudah diakses. Model estimasi terdiri dari 27 negara Uni Eropa dengan variabel yang diperoleh dari World Government Indicators (WGI) dan EU LGBT Survey. Mengapa Uni Eropa? Karena kita coba hilangkan faktor acak negara dengan membuatnya lebih berada pada “level permainan” yang sama.
Yang ingin kita lihat adalah bagaimana pengaruh dari sikap pro-LGBT suatu negara terhadap pertumbuhan ekonominya. Dari beragam variabel dalam survei tersebut, kita dapat mengonstruksi tiga hal yang paling relevan, di antaranya adalah: dukungan figur publik (baik politikus maupun artis), dukungan pemerintah, dan dukungan pemuka agama.
Model yang dibangun didasarkan pada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Dalam model ini, ekonomi dapat tumbuh dengan dengan bantuan modal dan tenaga kerja, yang berarti bahwa kecenderungan LGBT yang semakin besar di sebuah negara akan berdampak kepada kondisi kependudukan yang memburuk. Hal ini dapat dijelaskan dari fakta terang benderang bahwa pasangan LGBT tidak dapat menghasilkan keturunan. Kondisi kependudukan yang memburuk tersebut pada gilirannya akan menghambat ekonomi untuk terus tumbuh.
Negara-negara besar di Eropa seperti Jerman dan Perancis, misalnya, memiliki kecenderungan pertumbuhan populasi yang negatif. Akibatnya, pada tahun 2060, negara-negara ini dapat kehilangan hampir setengah penduduknya karena kondisi masyarakat yang pengalami penuaan dengan cepat (rapid aging society). Mau bukti? Lihat saja isi timnas Jerman dan Perancis yang mulai dari mulai penjaga gawang sampai strikernya didominasi oleh keturunan imigran. Lihatlah nama-nama mulai dari Zinedine Zidane, Marcel Desaily, Thierry Henry, Mehmet School hingga yang teranyar semisal Mamadou sakho, Eliqoium Mangala, Mesut Ozil, Ilkay Gundongan dan Lukas Podolski.
Sekarang kita kembali pada fokus tulisan, yakni apakah ada pengaruh dukungan terhadap LGBT pada pertumbuhan ekonomi? Singkat cerita, hasil pemodelan menunjukkan bahwa persentase dukungan figur publik terhadap LGBT yang semakin besar ternyata tidak berdampak signifikan tehadap pertumbuhan ekonomi. Dari sini tersirat bahwa meski figur publik berkoar-koar mendukung LGBT, hanya sedikit dari masyarakatnya yang betul-betul terpengaruh sehingga efek tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak terlalu kentara.
Penulis menemukan bahwa, jika melihat faktor pemerintah, setiap 1 persen kenaikan kecenderungan pro LGBT dapat mengakibatkan pelambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen. Oleh karena itu, peran pemerintah selaku pembuat kebijakan itu cukup krusial, baik itu bersifat pro maupun kontra terhadap LGBT. Dari sini pula, kita dapat melihat bahwa kebijakan pemerintah yang memiliki kecenderungan pro terhadap LGBT dapat menjadi kendala pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, pengaruh yang lebih besar didapat dari faktor pemuka agama, yaitu setiap 1 persen kenaikan kecenderungan pemuka agama yang pro terhadap LGBT dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang turun sebesar 0,12 persen dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari dua faktor yang disebut sebelumnya. Temuan ini tentunya menyiratkan bahwa pemuka agama adalah gerbang terakhir penjagaan sebuah negara terhadap LGBT.
Jika para pemuka agama kontra terhadap LGBT, sebagian besar masyarakat akan taat dan kecenderungan masyarakat yang berketurunan akan semakin banyak. Hal ini tentu pada gilirannya akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, semakin banyak pemuka agama yang pro-LGBT, atau bahkan menjadi pelaku LGBT itu sendiri (kalau ini yang terjadi niscaya jamaah di masjid bakal kocar-kacir), potensi “kehilangan generasi produktif” akan semakin besar.
Memang ada beberapa artikel ilmiah yang menunjukkan bahwa LGBT dapat mendorong kontrol populasi yang kemudian dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, alih-alih memajukan sebuah bangsa, kontrol yang berlebihan seperti ini justru akan menghancurkan potensi masa depan negara tersebut.
Tengok saja Tiongkok. Negara ini terkenal akan one child policy-nya (satu keluarga satu anak saja). Kebijakan itu terbukti sukses menekan populasi Tiongkok. Tapi coba lihat, dalam jangka panjang sekarang kebijakan tersebut malah menghancurkan mereka secara kependudukan sehingga mereka mengalami kondisi hard landing mulai tahun 2015. Contoh yang lebih ekstrem lagi tentu di negara-negara Eropa yang mewajarkan perilaku LGBT sehingga perilaku tersebut terus menjadi tren di negara-negara tersebut.
Jika para pemuka agama tidak dapat meyakinkan para pemangku kebijakan, mudah-mudahan tulisan ini dapat menuntun mereka untuk dapat berpikir lebih jernih dan rasional, bukan sekedar pakai ilmu kira-kira. Tentu Tuhan punya alasan mengapa menciptakan Adam dan Siti Hawa, bukan Adam dan Santo.
Catatan: Tulisan ini diterbitkan ulang dari selasar.com atas seizin penulis dengan beberapa penyesuaian kata-kata oleh editor majalah 1000guru.
Bahan bacaan:
- http://www.pewresearch.org/
Penulis:
Fithra Faisal Hastiadi, Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Kontak: fithra_faisal(at)yahoo.com